Hari-hari ini tidak sedikit dari kita mengeluhkan hal yang serupa tentang mengapa sains yang sudah jelas, didukung data kuat, dan disampaikan berulang kali oleh para pakar tetap berujung pada kekecewaan karena tidak dijadikan dasar utama kebijakan publik. Kita juga sebenarnya paham bahwa kebijakan publik tidak bekerja semata-mata berdasarkan kebenaran ilmiah, melainkan bergerak dalam logika politik.
Dua hal ini telah lama menjadi semacam “omon-omon” bersama. Namun keluhan itu seringkali keliru sasaran.
Kebijakan publik tidak terhenti karena ilmu pengetahuan gagal dikomunikasikan melalui komunikasi sains, melainkan karena ilmu pengetahuan masuk ke dalam sistem politik yang secara struktural tidak tunduk pada otoritas epistemik. Kesimpulan yang tidak nyaman ini muncul ketika komunikasi sains seharusnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai soal penyampaian pesan (translasi sains), melainkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan, tata kelola, dan konflik politik yang harusnya demokratis. Dalam kerangka ini, tudingan bahwa pembuat kebijakan “mengabaikan sains” justru salah memahami baik hakikat kebijakan publik maupun batas realistis dari apa yang dapat dicapai melalui komunikasi semata.
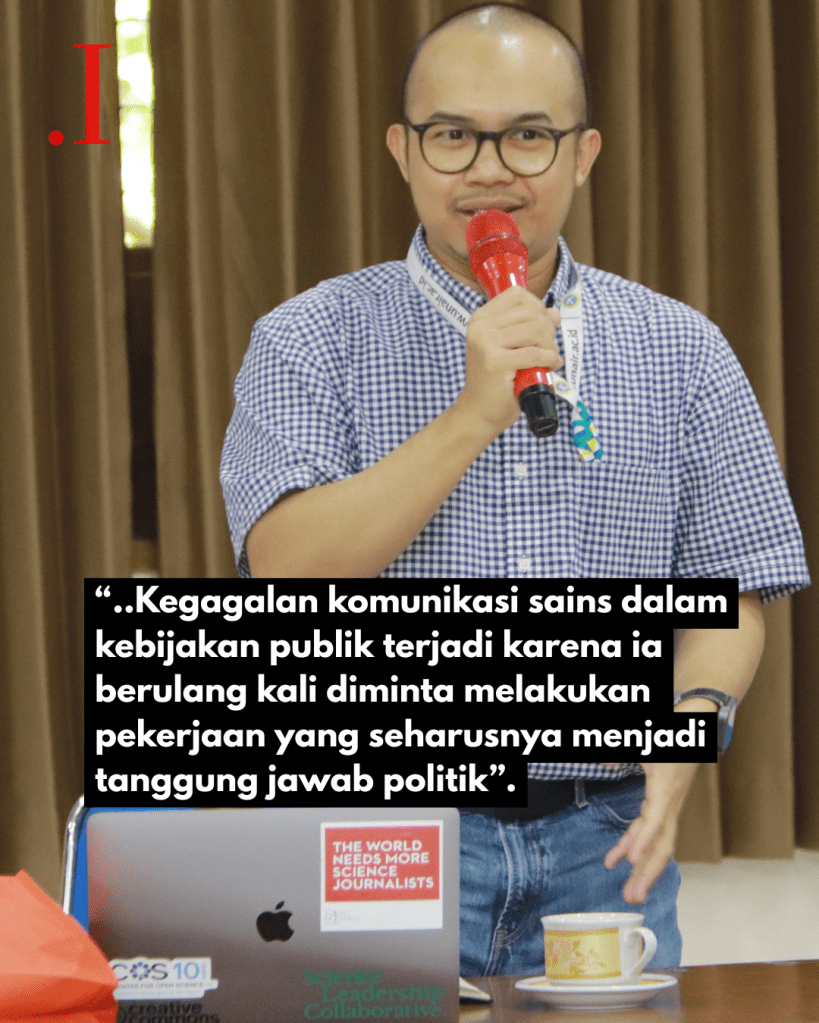
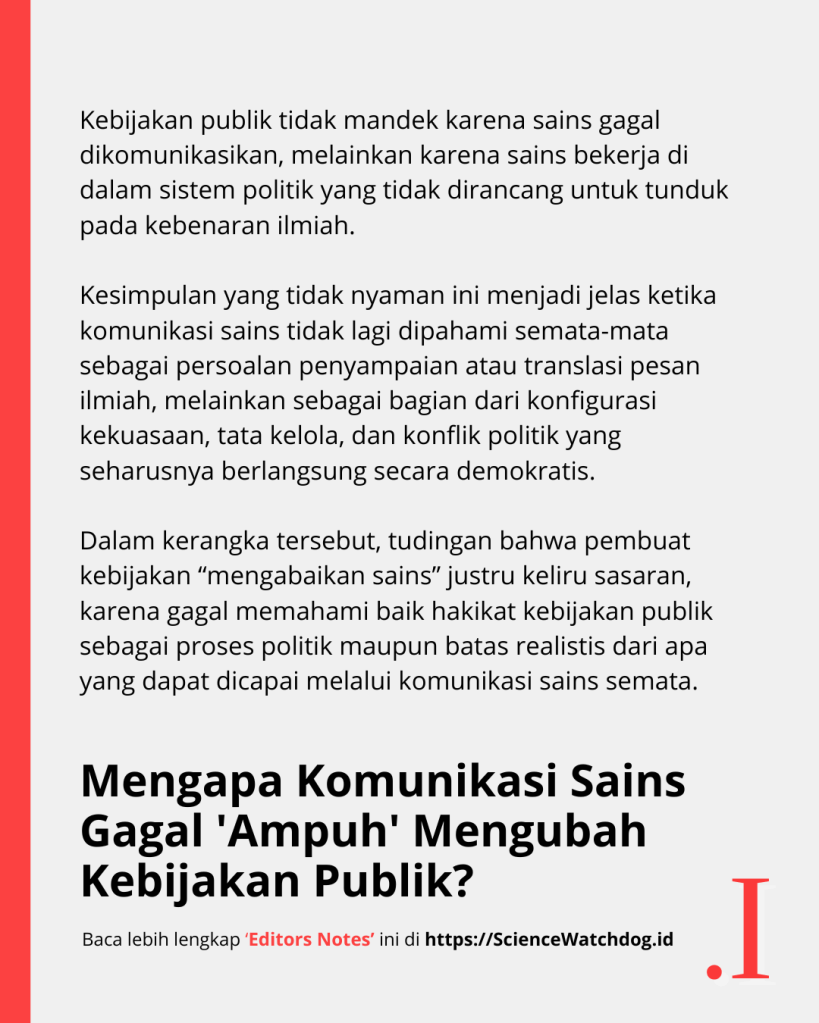
Dalam analisis kebijakan publik, proses perumusan kebijakan sejak awal tidak dirancang untuk memaksimalkan kebenaran ilmiah, melainkan untuk mengelola konflik antar aktor dan pemegang kepentingan. Sekalipun bukti ilmiah kerap dijadikan rujukan, dalam praktiknya ia jarang mendominasi keseluruhan proses hingga melahirkan kebijakan publik yang final. Regulator kebijakan bekerja sebagai penengah kepentingan yang saling bersaing dalam situasi kelangkaan sumber daya, ketidakpastian, dan keterbatasan politik.
Kebijakan publik tidak terhenti karena ilmu pengetahuan tidak dikomunikasikan dengan baik. Kebijakan publik terhenti karena ilmu pengetahuan masuk ke dalam sistem politik yang secara struktural acuh tak acuh terhadap otoritas epistemik. Ini adalah kesimpulan yang tidak nyaman yang muncul ketika komunikasi ilmiah tidak dilihat sebagai upaya penyampaian pesan, tetapi sebagai komponen dalam sistem kekuasaan, tata kelola, dan konflik demokratis. Klaim berulang bahwa pembuat kebijakan mengabaikan ilmu pengetahuan salah memahami baik apa itu kebijakan maupun apa yang dapat dicapai secara realistis melalui komunikasi.Pengetahuan ilmiah berfungsi memberi informasi dan memperjelas pilihan, tetapi tidak menentukan hasil akhir. Karena itu, ketika komunikasi sains diharapkan mampu secara langsung mendorong perubahan kebijakan, ia sebenarnya diminta untuk mengabaikan logika institusional yang secara mendasar bersifat non-epistemik. Ketidakselarasan inilah yang menjelaskan mengapa komunikasi sains kerap tampak gagal secara mencolok di titik pertemuannya dengan kebijakan publik. Kegagalan tersebut bukan terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada persoalan struktural khususnya sistem politik dan kekuasaan.
Dalam bahasa kebijakan, persoalan struktural pertama justru terletak pada cara frasa “kebijakan berbasis bukti” sering dipahami secara berlebihan. Dalam praktik, bukti ilmiah memiliki peran penting untuk menginformasikan dan membingkai pilihan kebijakan, tetapi kebijakan publik tidak pernah disusun hanya berdasarkan bukti ilmiah semata. Setiap keputusan kebijakan selalu membawa implikasi distribusional soal siapa yang menanggung biaya, siapa yang memperoleh perlindungan, dan siapa yang menanggung risiko.
Ilmu pengetahuan berperan krusial dalam memetakan konsekuensi tersebut secara semakin presisi dan transparan, namun penentuan prioritas sosial tetap melibatkan pertimbangan normatif dan politik yang berada di luar jangkauan sains itu sendiri. Karena itu, nasihat ilmiah diperlakukan oleh pembuat kebijakan sebagai salah satu masukan yang sangat penting di antara berbagai pertimbangan lain, seperti proyeksi ekonomi, insentif elektoral, batasan hukum, dan keberlanjutan institusional, tanpa mengurangi nilai strategis sains dalam proses pengambilan keputusan.
Komunikasi sains tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan dilema tersebut. Perannya lebih terbatas namun tetap penting, yakni membantu publik memahami pilihan yang tersedia secara rasional serta mendukung proses advokasi berbasis pengetahuan. Dalam konteks kebijakan, komunikasi sains kerap berfungsi sebagai pertimbangan eksternal yang memberi tekanan normatif dan informasional, bukan sebagai penentu langsung keputusan. Ketika kejelasan ilmiah justru meningkatkan biaya politik, resistensi hampir selalu menyusul. Dari sudut pandang ini, ketidakberanjakan kebijakan di hadapan bukti yang kuat bukanlah tindakan irasional, melainkan sering kali merupakan pilihan yang secara strategis rasional. Para pembuat kebijakan, yang sebagian besar merupakan aktor politik, cenderung membaca kebenaran ilmiah secara pragmatis melalui kalkulasi elektoral yang menguntungkan posisi mereka.
Namun terdapat pengecualian penting dalam lanskap politik kontemporer, terutama dalam konteks yang kerap diringkas dengan ungkapan no viral, no justice. Ketika isu ilmiah berhasil menembus ruang viral di media sosial dan memicu perhatian publik luas, kalkulasi politik dapat berubah secara drastis. Dalam situasi semacam ini, bukti ilmiah tidak bekerja melalui jalur rasional teknokratis, melainkan melalui tekanan visibilitas dan emosi kolektif. Hal ini semakin diperkuat oleh kecenderungan politisi menjadikan media sosial sebagai panggung performatif, tempat sikap, respons, dan klaim keberpihakan dipertontonkan secara terbuka. Pada titik ini, komunikasi sains dapat memperoleh daya dorong sementara, bukan karena ia mengalahkan logika politik, melainkan karena ia berhasil masuk ke dalam logika politik itu sendiri. Namun bahkan dalam pengecualian ini, sains tetap berfungsi sebagai instrumen dalam kalkulasi citra dan legitimasi, bukan sebagai penentu otonom arah kebijakan.
Masalah yang lebih mendasar muncul dari cara komunikasi sains terus dibingkai melalui logika defisit, yakni anggapan bahwa resistensi kebijakan terutama disebabkan oleh ketidakpahaman. Di balik kerangka ini tersimpan keyakinan implisit bahwa jika pembuat keputusan dan publik benar-benar memahami bukti ilmiah, mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama. Temuan empiris dalam psikologi politik dan komunikasi sains menunjukkan bahwa peningkatan literasi atau pemahaman ilmiah tidak selalu menyatukan sikap publik dan pembuat kebijakan terhadap isu-isu kontroversial. Studi yang lain juga menguatkan bahwa interpretasi bukti ilmiah dipengaruhi oleh motivasi kognitif dan nilai budaya, sehingga kelompok yang berbeda masih mempertahankan atau bahkan memperkuat posisi mereka meskipun tingkat pengetahuan sains meningkat, terutama pada isu yang terkait dengan identitas dan nilai sosial.
Setiap kebijakan menyentuh kepentingan yang tidak seimbang, menciptakan pemenang dan pihak yang harus menanggung beban. Konsekuensi semacam ini tidak dapat dinegasikan oleh komunikasi sains, betapapun jelas dan konsistennya bukti disampaikan. Menganggap perbedaan pandangan sebagai kegagalan komunikasi sains bukan hanya keliru secara analitis, tetapi juga menjamin situasi frustrasi yang berulang bagi para ilmuwan dan komunikator sains.Proses pembuatan kebijakan memang berlangsung tepat di titik-titik konflik nilai tersebut. Mitigasi perubahan iklim, regulasi kesehatan publik, perlindungan lingkungan, maupun persoalan bioteknologi tidak tersendat karena ketidaktahuan, melainkan karena konsekuensi distribusional yang menyertainya. Setiap kebijakan menyentuh kepentingan yang tidak seimbang, menciptakan pemenang dan pihak yang harus menanggung beban. Konsekuensi semacam ini tidak dapat dinegasikan oleh komunikasi sains, betapapun jelas dan konsistennya bukti disampaikan. Menganggap perbedaan pandangan sebagai kegagalan komunikasi sains bukan hanya keliru secara analitis, tetapi juga menjamin situasi yang frustrasi berulang bagi para ilmuwan (komunikator sains).
Keterbatasan berikutnya terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan dalam arena kebijakan. Komunikasi sains kerap berangkat dari asumsi bahwa argumen bersaing berdasarkan kualitas dan kekuatan bukti. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak bekerja sebagai “pasar ide dan gagasan”. Bukti ilmiah dimobilisasi secara strategis oleh aktor-aktor dengan akses yang tidak setara terhadap pengambil keputusan. Kapasitas lobi, penangkapan regulasi, pengaruh media, serta kedekatan institusional menentukan pengetahuan mana yang memperoleh ruang dan mana yang tersingkir.
Dalam konteks diatas, kualitas komunikasi sains sering kali kalah penting dibandingkan keselarasan politik. Bukti yang menantang kepentingan kuat dapat diakui secara formal, tetapi kemudian dikesampingkan, sementara bukti yang selektif atau lemah justru memperoleh pengaruh besar ketika mendukung agenda yang telah mapan. Komunikasi sains tidak dapat memperbaiki ketimpangan ini tanpa perubahan relasi kekuasaan itu sendiri, dan mengharapkan hal tersebut terjadi semata-mata melalui komunikasi adalah naif secara analitis.
Desain institusional semakin mempersempit dampak kebijakan dari komunikasi sains. Dalam banyak sistem politik, nasihat ilmiah bersifat konsultatif, bukan mengikat. Komite ahli, konsultasi publik, dan tinjauan bukti menciptakan ruang untuk mendengarkan tanpa mewajibkan tindak lanjut. Justru karena desain ini menjaga fleksibilitas politik, ia menjadi menarik bagi regulator kebijakan. Akibatnya, terbentuk siklus performatif seolah sains sudah dikonsultasikan, dikomunikasikan, dan dikutip, sementara keputusan kebijakan berjalan nyaris tanpa perubahan berarti. Komunikasi sains kemudian dipuji sebagai inklusif dan transparan, meskipun pengaruh substantifnya sangat terbatas. Dalam sistem struktural yang timpang semacam ini, komunikasi sains lebih berfungsi sebagai alat legitimasi ketimbang sebagai pendorong hasil kebijakan.
Dinamika ini terlihat jelas dalam praktik komunikasi sains partisipatif. Pelibatan publik sering dipromosikan sebagai upaya mendekatkan sains dengan demokrasi (i.e sering disebut demokratisasi sains). Usaha inni memang dapat meningkatkan legitimasi prosedural, memperkuat “persepsi” keadilan, dan meredakan konflik terbuka. Namun bukti empiris bahwa partisipasi semacam ini secara konsisten mengubah keputusan kebijakan, masih sangat tipis. Tanpa komitmen institusional untuk bertindak berdasarkan hasil partisipatif, keterlibatan publik berhenti sebagai pemenuhan ekspresi publik, bukan menuju upaya transformasi kebijakan publik yang lebih demokratis. Sehingga akan lagi-lagi berakhir seperti “publik berbicara, institusi mendengarkan, tetapi distribusi kekuasaan tetap tidak berubah”.
Yakin akan begitu. Selalu begitu.
Tekanan waktu memperparah keterbatasan tersebut. Pengetahuan ilmiah terakumulasi secara perlahan dan mengakui kemungkinan revisi. Sebaliknya, kebijakan sering bergerak di bawah urgensi yang dipicu siklus Pemilihan Umum (Pemilu), krisis, dan dinamika media. Dalam kondisi semacam ini, kepastian politik cenderung lebih dihargai daripada kehati-hatian epistemik. Komunikasi sains yang menekankan ketidakpastian dan batas pengetahuan kesulitan bersaing dengan narasi yang menjanjikan kontrol dan kesegeraan. Situasi Pandemi memperlihatkan ketidaksinkronan ini secara gamblang. Ketika nasihat ilmiah berubah seiring bukti baru sebagai sifat sains bekerja, hal tersebut kerap dibingkai sebagai kebingungan, sementara pesan politik yang memproyeksikan keyakinan memperoleh ganjaran dari publik, sekalipun situasinya akan terpolarisasi. Banyak pemerintah merespons bukan dengan memperkuat integrasi bukti ke dalam kebijakan, melainkan dengan memperketat disiplin pesan, yang meningkatkan kepatuhan jangka pendek sekaligus mengikis kepercayaan jangka panjang terhadap kejujuran ilmiah.
Faktor lain yang sering luput diperhatikan adalah ketidaksesuaian sasaran audiens. Komunikasi sains kerap diarahkan kepada publik luas dengan harapan tekanan opini akan diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan. Padahal keputusan kebijakan dibuat oleh kelompok kecil dalam struktur birokrasi dan legislatif. Aktor-aktor ini lebih responsif terhadap kepentingan terorganisir, norma institusional, dan koalisi politik daripada tingkat pemahaman publik secara umum. Komunikasi sains yang memprioritaskan jangkauan massal, tetapi mengabaikan jalur pengaruh institusional, sering kali berbicara keras ke arah yang keliru.
Jurang budaya profesional memperlebar masalah tersebut. Ilmuwan dilatih untuk menghindari klaim normatif dan menekankan ketidakpastian, sementara pembuat kebijakan dituntut membenarkan keputusan dalam kerangka moral, ekonomi, dan politik. Ketika komunikasi sains terlalu teknis dan menjauh dari bahasa nilai, ia gagal masuk ke dalam perdebatan kebijakan. Namun ketika ia mengadopsi kerangka persuasif atau moral, ia berisiko dicap sebagai advokasi. Ruang terjemahan yang efektif di antara dua dunia ini sempit dan secara struktural tidak stabil.
Namun, di atas semua itu, terdapat kecenderungan persisten untuk menjadikan komunikasi ilmiah sebagai mekanisme perbaikan atas defisit demokrasi. Ketika kepercayaan publik menurun atau kebijakan gagal, komunikasi sains diperkuat. Tanggung jawab pun bergeser dari tata kelola ke pesan (translasi sain). Masalah struktural seperti kritik terhadap regulasi, relasi kekuasaan, lemahnya akuntabilitas, dan penegakan hukum yang rapuh direduksi menjadi persoalan ketidakpahaman publik. Komunikasi sains lalu menjadi respons berbiaya rendah terhadap kegagalan politik yang biayanya jauh lebih tinggi.
Penilaian yang lebih realistis perlu dimulai dengan redefinisi keberhasilan. Komunikasi sains tidak seharusnya diukur dari kemampuannya menghasilkan perubahan kebijakan langsung, karena itu merupakan hasil politik. Ia lebih tepat dinilai dari kemampuannya menjelaskan bukti, mengungkap pertukaran kepentingan, mendokumentasikan ketidakpastian secara jujur, dan membuat proses pengambilan keputusan lebih transparan. Kontribusi ini penting, tetapi bekerja secara tidak langsung dan dalam jangka waktu panjang.
Jika ilmu pengetahuan ingin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kebijakan publik, bebannya tidak dapat diletakkan pada cara para ilmuwan berkomunikasi sains semata. Terlebih lagi, tanggung jawab itu tidak seharusnya dibebankan kepada para ilmuwan sebagai aktor komunikasi sains, seolah-olah hanya mereka lah yang layak memikul kewajiban moral untuk menambal erosi demokrasi dan kemunduran kebijakan berbasis bukti.
Reformasi institusional justru menjadi prasyarat utama. Ini mencakup kewajiban yang lebih jelas bagi regulator kebijakan untuk menjelaskan dan membenarkan penyimpangan dari nasihat ilmiah, integrasi bukti yang lebih kuat dan konsisten dalam proses regulasi, serta mekanisme yang mampu menyingkap peran kepentingan dalam membentuk keputusan publik. Tanpa perubahan semacam ini, komunikasi sains akan terus diposisikan sebagai pengganti kehendak politik. Kegagalannya bukan karena komunikasi sains tidak berfungsi, melainkan karena ia berulang kali diminta melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab politik.

